Wawancara J Anto dengan Didi Kwartanada:
DIDI Kwartanada adalah alumnus Jurusan Sejarah UGM (angkatan 1986) yangMenekuni sejarah etnis Tionghoa di Indonesia, khususnya Jawa. Ia menempuhPendidikan sejarah di UGM dan National University of Singapore (NUS), juga sempat menjadi asisten peneliti di Waseda Institute of Asia Pacific Studies (WIAPS), Tokyo. Karya-karyanya, baik yang bersifat akademis– artikel jurnal, bab dalam buku serta pengantar buku, maupun yang populer – telah terbit dalam bahasa Inggris, Jerman,Jepang, Mandarin, Belanda, dan Indonesia. Didi Kwartanada juga duduk dalam kepengurusan pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) 2016-2021. Berikut wawancara denganDirektur Yayasan NationBuilding (NABIL) di Jakarta itu.
Pandangan umum masyarakat beranggapan bahwa saat revolusi fisik masyarakat Tionghoa memihak Belanda, menurut Anda benarkah seperti itu fakta sejarahnya?
Tentu pandangan itu sangat generalis, menyederhanakan masalah dan tidak betul. Kalau dibilang “memihak Belanda”, toh juga tidak 100% bumiputra Indonesia “memihak Republik Indonesia”. Misalnya tentara KNIL yang hendak menjajah kembali RI yang baru saja lahir itu mayoritas anggotanya justru bukan Belanda. Kembali ke soal etnis Tionghoa dan revolusi Indonesia, sikap mereka pada saat itu merupakan hasil produk kebijakan-kebijakan kolonial Belanda dan militerisme Jepang ditambah “swa-segregasi” di bidang politik yang terjadi di masa pergerakan nasional, yang dilakukan oleh kelompokBumiputra maupun Tionghoa sendiri.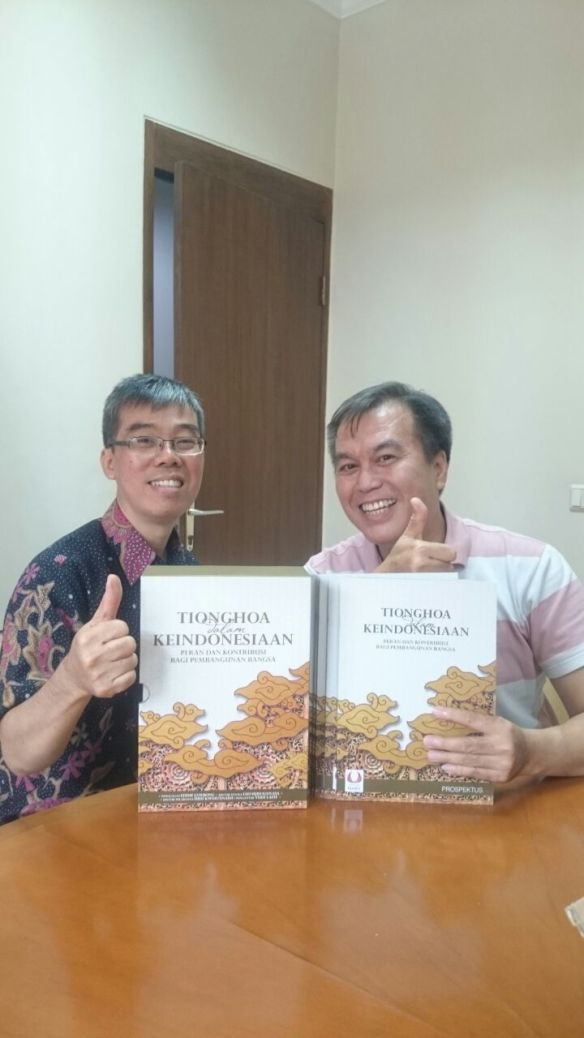 Seperti kita ketahui, kolonial BelandaSeperti kita ketahui, kolonial Belanda membagi masyarakat Hindia Belanda ke dalam tiga golongan hukum: (1) Eropa, (2) Timur Asing dan yang paling bawah (3) Inlander (Bumiputra). Tionghoa sebagai golongan “middlemen” (perantara) masuk di ranah Timur Asing. Konsekuensinya, secara hukum mereka di atas bumiputra, maka hanya sebagian kecil Tionghoa yang mau jadi “pelompat pagar” di masa pergerakan untuk menyamakan dirinya dengan Bumiputra. Di pihak lain, harap diingat, pada masa pergerakan nasional, wacana nasionalisme yang dianut kebanyakan organisasi politik masih berupa “etno nasionalisme”, tidak semua partai politik menerima non-bumiputra sebagai anggota penuh. Hanya Indische Partij (1913), PKI (1920) dan Gerindo (1937) saja! Ini mesti diingat!
Seperti kita ketahui, kolonial BelandaSeperti kita ketahui, kolonial Belanda membagi masyarakat Hindia Belanda ke dalam tiga golongan hukum: (1) Eropa, (2) Timur Asing dan yang paling bawah (3) Inlander (Bumiputra). Tionghoa sebagai golongan “middlemen” (perantara) masuk di ranah Timur Asing. Konsekuensinya, secara hukum mereka di atas bumiputra, maka hanya sebagian kecil Tionghoa yang mau jadi “pelompat pagar” di masa pergerakan untuk menyamakan dirinya dengan Bumiputra. Di pihak lain, harap diingat, pada masa pergerakan nasional, wacana nasionalisme yang dianut kebanyakan organisasi politik masih berupa “etno nasionalisme”, tidak semua partai politik menerima non-bumiputra sebagai anggota penuh. Hanya Indische Partij (1913), PKI (1920) dan Gerindo (1937) saja! Ini mesti diingat!
Bahkan Partai Nasional Indonesia (1927)-nya Sukarno cs, hanya menerima Tionghoa sebagai anggota luarbiasa, alias tidak diterima sepenuhnya. Di pihak lain, orang Tionghoa pun juga punya organisasi politiknya sendiri, seperti Chung Hua Hui (CHH) yang pro Belanda, maupun kelompok Sin Po yang condong ke Tiongkok. Ada Partai Tionghoa Indonesia (1932) pimpinan Liem Koen Hian yang gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, bahkan mengilhami etnis Arab untuk ikut mengikuti jejak mereka, dengan berdirinya Persatuan Arab Indonesia (1934). Liem ini sudah “berdarah-darah” memihak Indonesia, namun dalam kenyataannya, dia banyak mengalami penolakan dari pihak Bumiputra, sehingga dengan penuh kekecewaan dia melepaskan kewargenagaraan Indonesia yang diperjuangkannya, dan akhirnya wafat di Medan (1952) sebagai WNA .
Segregasi zaman Belanda ini kemudian diperkuat oleh kebijakan Jepang yang juga memisah-misahkan kelompok etnis demi mengekalkan kekuasaannya. Bahkan kata Sjahrir dalam tulisannya “Perdjoeangan Kita”, Jepang mengajarkan kepada bumiputra, bahwa semua etnis mesti dibenci kecuali Bumiputra dan Jepang itu sendiri. Dengan latar belakang itulah, maka sikap etnis Tionghoa terpecah menjadi tiga di masa revolusi: (1) bersikap netral (ini bukan masalah kami, ini masalah RI vs Belanda) bisa dibilang, inilah sikap mayoritas etnis Tionghoa; (2) mengharapkan pulihnya “zaman normal”. Ini adalah cerminan sikap “middlemen” yang bisnisnya tergantung pada kamtibmas; dan (3) memihak perjuangan RI, menariknya, sikap ini bukan hanya diambil oleh kaum peranakan, tapi cukup banyak juga dari kalangan Tionghoa totok, termasuk kaum perempuannya. Tiga pilihan sikap tadi barangkali juga muncul di berbagai kelompok masyarakat lainnya, bukan hanya Tionghoa.
Harap diingat, saat ini satu-satunya pahlawan nasional dari etnis Tionghoa adalah Laksamana Muda TNI AL (Purn.) John Lie (nama lengkapnya Lie Tjeng Tjoan, asal Manado). Beliau diangkat sebagai pahlawan nasional oleh Presiden SBY pada 2009, atas jasanya sebagai kapten kapal TNI AL di masa revolusi fisik, sekaligus salah satu tokoh pembangun TNI AL. Bahkan sebagai tanda hormat, TNI AL menabalkan namanya sebagai KRI John Lie 358. Jadi intinya, sejarah tidak bisa digeneralisasikan, dan tuduhan di atas tadi tidak betul,
Apakah narasi buku teks sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah sudah cukup memadai memberi ruang terhadap peran terhadap orang Tionghoa yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan?
Setahu saya belum ya. Tapi sudah lama saya tidak mengecek buku pelajaran sekolah. Saya penasaran, apakah John Lie selaku pahlawan nasional RI, perjuangannya sudah masuk. Tapi saya ingat, kira-kira sepuluh tahun silam, saya pernah menemukan tokoh-tokoh Tionghoa dalam dunia sastra, seperti Kwee Tek Hoay, sudah masuk dalam buku teks sejarah SMA. Itu sudah satu kemajuan besar, menurut saya. Namun akan lebih lengkap lagi, jika sumbangsih etnis Tionghoa dalam perjuangan di masa revolusi fisik juga disinggung dalam buku teks sejarah di sekolah. Paling tidak, peran John Lie bisa ditampilkan.
Dari pembacaan Anda, apakah sebelum revolusi fisik, sudah adakah keterlibatan orang Tionghoa dalam perjuangan membela penguasa-penguasa lokal melawan kolonial Belanda? Misalnya di Jawa atau Aceh?
Kalau di Aceh saya kurang tahu. Tapi di Jawa, khususnya di masa 170-1743 orang-orang Tionghoa di bawah pimpinan Kapitan Sepanjang (Souw Pan Jiang) dan Tan Sin Ko (alias Singseh) bersekutu dengan laskar kerajaaan Mataram pimpinan Mas Garendi dan Mas Said untuk bersama-sama angkat senjata melawan VOC (Kumpeni). Dari buku karya Daradjadi berjudul “Geger Pacinan” terungkap bahwa medan perang yang mereka kobarkan itu lebih luas daripada Perang Jawa-nya Diponegoro (1825-1830). Perang yang dimulai di daerah Gandaria di pinggiran Batavia kemudian membakar hampir seluruh wilayah pantai utara dan pedalaman Jawa, hingga ke Pasuruan di ujung timur Jawa. Laskar gabungan ini mampu merebut istana Kartasura, sehingga Sultan Pakubuwono II yang memihak Belanda terpaksa lari minta perlindungan VOC. Sayang sekali, waktu itu para penguasa lokal masih bisa dipecah-belah Belanda. Akhirnya VOC dengan dukungan Sultan Pakubuwono II, laskar Madura dan Bugis, mampu mengalahkan laskar gabungan Jawa-Tionghoa tersebut. Untuk mengabadikannya, kini di TMII dibuatkan monumen untuk mengenang perjuangan laskar Jawa dan Tionghoa tersebut.
Pada umumnya peran orang Tionghoa saat menjadi tentara pejuang membantu suplai logistik tentara atau laskar, benarkah?
Memang secara umum bantuan orang Tionghoa di masa revolusi nampak di bidang logistik, mulai dari penyediaan suplai senjata, amunisi, obat-obatan hingga dapur umum. Dalam bidang ini peran orang-orang Tionghoa totok (khususnya dari luar Jawa) cukup menonjol. Misalnya almarhum Tani (Tan Tiong Siok) asal Medan yang baru saja wafat kemarin. Hebatnya, pak Tani itu mendapatkan Bintang Gerilya, bintang tertinggi dari masa revolusi kemerdekaan. Harap diingat, tidak sembarang orang memiliki penghargaan ini, sehingga beliau berhak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Di Jawa pun cukup banyak orang Totok, khususnya dari kelompok dialek Hokchia, yang mendukung suplai logistik, seperti yang sudah diteliti oleh sejarawan Singapura, Twang Peck-yang, dalam bukunya “Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950”. Taipan Liem Sioe Liong (alm.) adalah salah satu contoh yang paling terkenal. Namun dari penelurusan yang saya lakukan, ada beberapa orang Tionghoa yang tewas di tembak Belanda saat mereka bergabung dengan laskar bersenjata RI. Contoh pertama adalah “Sing” atau “A Sing” seorang anggota laskar rakyat di Palembang yang tewas terkena peluru Belanda saat Pertempuran Lima Hari di sana. Kisahnya diceritakan oleh Makmun Morod, komandannya Sing, yang kemudian menjadi salah satu tokoh terkemuka TNI AD. Di Taman Makam Pahlawan (TMP) Jurug Surakarta, ada makam Sie King Lien (Ferry), pemuda anak orang kaya yang bergabung dengan Tentara Pelajar Surakarta. Ferry tewas ditembak Belanda saat menempel poster anti Belanda. Tidak hanya lelaki saja yang berani mengambil risiko. Perempuan Tionghoa pun tidak ketinggalan ikut menempuh bahaya, seperti saudari-saudari bumiputranya. Ho Wan Moy (Tika Nurwati), seorang anggota LVRI, dikenang sahabat-sahabatnya sebagai “seorang Srikandi”, seorang mata-mata pemberani bagi Republik. Jadi darah Tionghoa pun ikut membasahi bumi pertiwi ini. Mereka pun ikut menegakkan NKRI dengan darah, keringat dan airmata!
Dimuat Analisa Minggu 24 September 2017 http://harian.analisadaily.com/assets/e-paper/2017-09-24/files/mobile/6.jpg




